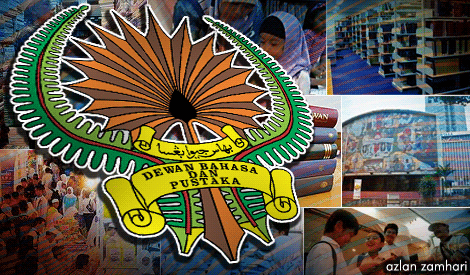Ia adalah sebuah bangunan dua tingkat yang gah - jika dilihat pada konteks masa itu. Ingatan terhadap pejabat atau kedai apa yang mengisinya sudah agak kabur.
Apa yang pasti ada dua kedai di situ yang kekal dalam ingatan. Satu, kedai tukang jam milik usahawan Melayu di tingkat bawah. Di tepi bangunan MARA di Jalan Ah Cheong itulah yang lebih menarik. Ada kedai buku Buyong Yunos.
Bagi sebuah bandar sesederhana Teluk Intan, kedai buku itu - bagi penggemar buku dan aktiviti membaca - adalah 'syurga'. Ia menjadi lebih nikmat kerana di situlah bahan-bahan bacaan terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) dapat ditemui.
Dewan Masyarakat yang mencerdaskan, Dewan Budaya yang mencelikkan, Dewan Sastera yang mengagumkan. Tidak ketinggalan Pelita Bahasa yang mengasyikkan, juga Dewan Pelajar yang mencerahkan pemikiran.
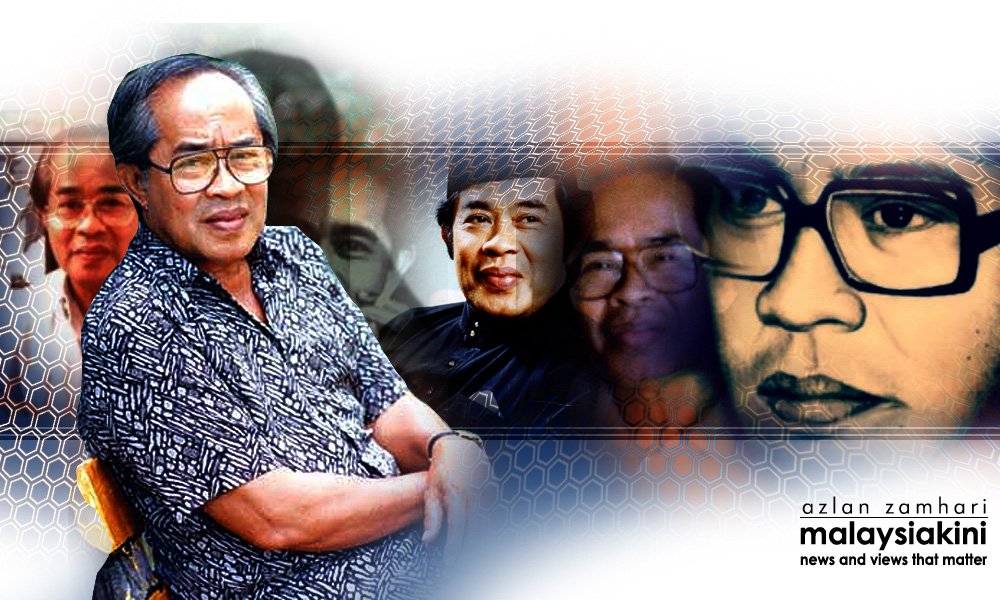 Itu belum lagi buku-buku terbitan lain DBP. Koleksi drama dan sajak Sasterawan Negara Usman Awang misalnya. Novel sekian ramai penulis atau nama besar dalam bidang persuratan, serta buku-buku ilmiah.
Itu belum lagi buku-buku terbitan lain DBP. Koleksi drama dan sajak Sasterawan Negara Usman Awang misalnya. Novel sekian ramai penulis atau nama besar dalam bidang persuratan, serta buku-buku ilmiah.
Menyentuh naskhah-naskhah itu adalah keriangan sukar digambarkan. Membelek dan membacanya sambil menunggu bas atau dalam perjalanan pulang dari sekolah pula adalah pengalaman yang mendewasakan.
Itu cerita kira-kira 30 tahun silam.
Hari ini DBP genap berusia 60 tahun. Jika DBP adalah manusia, ia sudah menjadi orang veteran yang kaya pengalaman. Namun DBP bukan manusia tetapi sebuah agensi kerajaan terletak di bawah Kementerian Pendidikan.
Usia 60 tahun - bagi sebuah badan kerajaan - sepatutnya menjadikan ia begitu matang. Selepas menempuh pelbagai perkembangan semasa tentu banyak yang dapat dipelajarinya. Atau sekurang-kurangnya ia sepatutnya begitu.
Hari ini kedai buku Buyong Yunos di Teluk Intan itu rasanya sudah tinggal nama. DBP pula semacam tertinggal kereta api.
Melihat DBP sebagai 'manusia' adalah seperti memandang Sangeetha ciptaan allahyarham Azizi Abdullah - renta dan pikun.
Khabarnya juga, untuk mencari majalah Dewan Masyarakat, Dewan Sastera, Pelita Bahasa, Dewan Budaya itu pula hampir-hampir sama seperti mencari lailatulqadar. Ada, wujud tapi entah bila dan di mana. Dan kita perlu berteka-teki untuk menemuinya.
(Lalu kamu pun berkata: "Ia sebenarnya ada. Hendak seribu daya tak hendak seribu dalih," kan?)
DBP sokong DLP
Suatu ketika dulu, ingatan terhadap DBP adalah kenangan cerita tentang syarikat Dawama dan sakitnya pekerja di situ dan keanehan operasi pengurusan buku teks.
Ia berbeza dengan DBP sebelum itu. Ia menjadi organisasi yang dibanggakan. Orang di dalam badan itu didengari cakapnya, kempen dan gerak kerjanya diikuti dengan minat yang bersungguh.
Penulis, budayawan dan sasterawan menjadi pembawa pencerahan dari dalam DBP. Aktiviti keseniannya dihormati. Memang begitulah sepatutnya. Selain menguruskan buku teks sekolah, kegiatan kebudayaan dan kesusasteraan begitu subur di DBP.
 Selepas 60 tahun kita pun diberitahu bahawa DBP - yang ditubuhkan untuk mengembangkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara - menjadi penyokong Program Dwibahasa (DLP) dalam pembelajaran sekolah kerajaan.
Selepas 60 tahun kita pun diberitahu bahawa DBP - yang ditubuhkan untuk mengembangkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara - menjadi penyokong Program Dwibahasa (DLP) dalam pembelajaran sekolah kerajaan.
Penulis, Pyanhabib, berkata kesuraman DBP boleh dikatakan bermula selepas zaman Datuk Jumaat Mohd Nor menjadi ketua pengarahnya.
"Hari ini kita rasa kasihan sebab ramai penulis dan orang sastera seakan-akan menjauhi DBP.
"Suatu ketika dulu, sehari tidak menjenguk DBP kami rasa seperti ada yang tidak kena dalam aktiviti harian kami. Di situ kami bertemu kawan-kawan penulis, menonton teater, beraktiviti di sudut penulis.
"Tetapi selepas Datuk Jumaat tiada, DBP macam sudah jadi petaka," katanya.
Memang ada benarnya. Di mata orang awam kelihatan DBP secara perlahan-lahan menjadi tempat pelaksanaan percaturan politik pihak tertentu.
Mula-mula memanglah tidaklah ketara mana. Seperti angin sepoi-sepoi bahasa saja layaknya. Kemudian ia mula dilihat lebih terbuka apabila - misalnya - lantikan ke jawatan ketua pengarah semakin menghairankan, seolah-olah orang budaya dan sastera semuanya tidak cerdik untuk menduduki jawatan berkenaan.
Pada masa sama martabat bahasa Melayu semakin dipertanyakan. Selain DLP penggunaan nama dan istilah asing begitu meluas digunakan sehingga kita pun tertanya-tanya, apakah DBP masih menyedari bahawa mereka sebenarnya memiliki bidang kuasa tertentu untuk mengawal dan menghukum?
(Kemudian kamu pun berkata: "Tugas DBP sebenarnya lebih kepada mendidik, bukan menghukum," kan?)
Menteri berbahasa rojak
Ketika penggunaan bahasa Melayu yang lihai semakin perlu diperluaskan DBP tampil dengan 'fatwa' menyukarkan. Sibuk membezakan "baru" dengan "baharu" ketika ungkapan yang memiliki suku kata lebih ringkas sebenarnya adalah jauh lebih penting untuk pengembangan bahasa, misalnya.
Atau DBP tiba-tiba berasa ingin berseteru dengan penerbitan mandiri ketika minat membaca masyarakat terus berkembang dengan penerbitan buku oleh syarikat kecil atau sederhana.
Semalam Sasterawan Negara Datuk Kemala juga mengeluh.
Sambil mengucapkan tahniah sempena 60 tahun DBP Kemala menegur kemahiran berbahasa menteri pendidikan.
"Tahniah DBP (hari ulang tahun) 60 tahun tapi menteri pendidikan menjawab dengan bahasa rojak apabila ditemu ramah.
"Baru berucap mahu daulatkan bahasa Melayu. Berilah contoh yang baik pak menteri. Mahu ke mana Malaysia?" katanya di Facebook.
Era pak-pak menteri berbahasa dengan berhemah dan bermartabat sudah lama berlalu rupanya.
Lalu kita pun boleh bertanya: Mahu ke mana DBP?
Rasanya soalan itu bukan kali pertama dibangkitkan. Sudah lama dan ditimbulkan oleh pelbagai pihak namun pada usianya 60 tahun DBP - dalam keadaannya sekarang - semakin dipertanyakan sama ada masih relevan atau tidak untuk wujud sebagai badan penjaga serta pengembang bahasa Melayu.
Justeru dalam keadaan sekarang, terasa seperti sukar benar mencari ayat tanya, ayat seru atau ayat penyata yang tidak klise untuk dikemukakan kepada DBP.
Semoga nasib DBP tidak menjadi seperti kedai buku Buyong Yunos itu. Hanya segar dan mekar dalam kenangan.